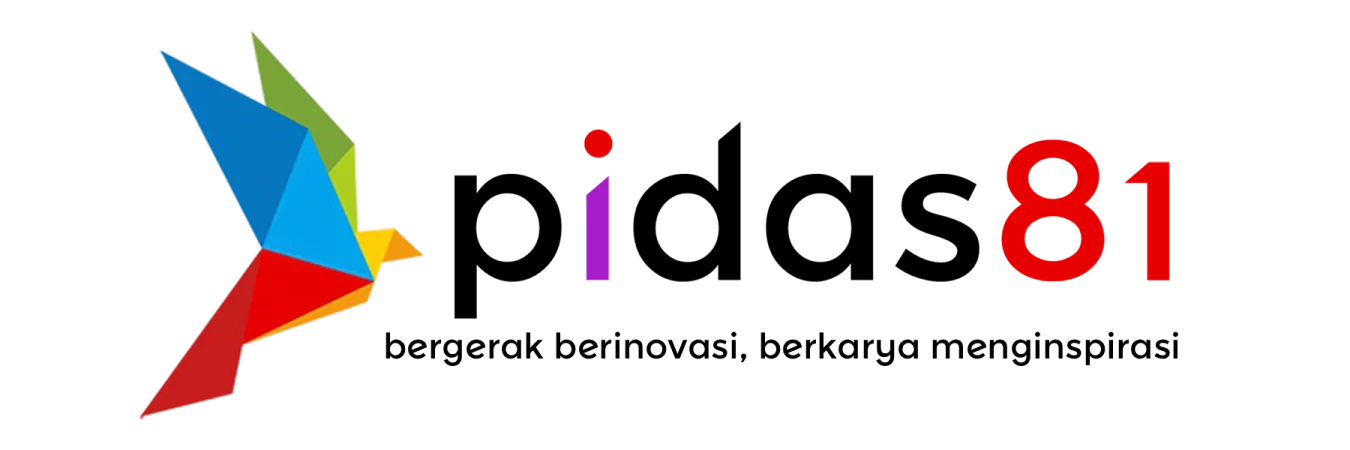Pendakian Kedua | 4 Juli 2013
Sekitar pukul 5 pagi kami semua diharuskan bangun, yang sudah benar-benar melek membangunkan yang kembali tertidur. Saya termasuk ke golongan yang kembali tidur. Tertidur duduk. Saya kembali dibangunkan, dan kami semua membereskan barang-barang bawaan. Setelah itu tenda pun segera dibongkar, pasak-pasak dicabut, matras-matras digulung, yang menganggur menyuapi yang bekerja dengan biskuit-biskuit pula mengoper gelas berisi susu jahe panas yang sudah diseduh Akrima.
Semua beres pada pukul setengah 8 pagi, kami pun siap berangkat lagi. Sinar matahari melumuri permukaan kulit saya melalui radiasinya, menyulut semangat saya kembali. Kami mendaki melalui medan yang saya sudah saya deskripsikan sebelumnya, curam, tanah dan akar yang saling menjalin, namun tidak selicin kemarin, karena air hujan sudah berkurang di permukaan tanah.
Sekitar setengah jam setelahnya, kami tiba di jalan ular, itu sebutan dari Akrima. Kalau saya sendiri menyebutnya dengan jalan titian kabut. Titian kabut adalah bagian dari puncak Gunung Gede—ya, kami telah tiba dipuncaknya. Titian kabut itu merupakan jalan yang terbagi tiga jalur sempit, sebelah kiri jalur yang berupa tanah pasir bergejolak yang sebelah kirinya merupakan jurang, makanya diberi pagar berupa 3tiga kabel tebal yang saling melilit. Jalur yang tengah berupa cekungan seperti parit kecil kering yang isinya bertaburan batu-batu besar. Jalur yang kanan, bukan pilihan, hampir menyerupai jalur yang kiri namun tidak memiliki pagar untuk melindungi kita dari jurang disebelah kanannya. Kami memilih jalur kiri.
Saya menikmati perjalanan di sini, di sebelah kiri walaupun di bawah jurang, tapi bila saya melihat atas dapat saya lihat pemandangan yang sangat indah. Bau sulfur mulai menjalar menelusup lubang hidung, tapi baunya tidak menyengat. Pak Suryo membuat saya merenung tentang pekerja yang dengan luar biasanya membuat pagar kabel ini, pagar kabel yang melindungi kami. Kadar oksigen semakin menipis seiring pendakian kita ke puncak, nafas saya enggak tersengal tapi saya merasa cukup sesak. Tapi saya enggak peduli. Saya lihat sekeliling mulai tumbuh bunga-bunga Edelweis, bunga keabadian, lestari. Sejujurnya saya nggak terlalu terkesan sama wujud bunga itu, wujudnya enggak manis, enggak elegan, namun memang terkesan kuat dan bertahan.
Pencapaian
Akhirnya, teman-teman, pada pukul 8.50 kami bersebelas sampai di maha puncak Gunung Gede, kami berada di 2.958 meter di atas permukaan laut. Walaupun kami enggak berhasil mendapat sunrise—yang dikejar seluruh pendaki di puncak—kebahagiaan saya tetap enggak bisa dipungkiri! Ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup saya banggakan. Di sana, Akrima membuat victory drink, yang merupakan minuman ritual anak Carve bila sampai puncak. Sesungguhnya victory drink hanyalah nata de coco dicampur beberapa sachet Nutrisari. Ya, di gunung kebahagiaan itu menjadi sangat sederhana. Setelah menggelar matras, kami duduk melingkar, menggilir mangkuk logam berisi victory drink.
Ule yang merupakan anggota baru Carve, disematkan sehelai slayer milik Adit, yang lain menyaksikan, beberapa mengibarkan bendera Carvedium di belakangnya. Saya, yang hanya seorang penyimak dan pencatat di sini, mengabadikan momen sakral mereka dengan kamera. Saya merasakan keharuan dan kemenangan pribadi menyaksikan para pecinta alam yang berhati mulia itu menikmati pencapaian ini dengan cara mereka sendiri.
Kembali Turun
Sekitar pukul 9.50 kami pun melanjutkan perjalanan kami menuruni puncak gunung—menuju kaki gunung. Turun gunung merupakan hal yang sebenarnya lebih mudah daripada mendaki, karena tidak menguras tenaga, tidak menantang gravitasi. Tapi, jalan menurun membutuhkan pikiran yang lebih siaga, karena bagaimanapun juga kekuatan mengontrol kaki sangat penting supaya enggak tergelincir. Adit mengingatkan supaya kita fokuskan kekuatan otot paha, bukan betis bukan dengkul, karena otot betis dan dengkul mudah tertarik. Fatah juga mengingatkan saya supaya memiringkan telapak kaki saya keluar, supaya luas penampang untuk menahan beban badan menjadi luas, bukan panjang.
Kami tiba di sebuah ladang rumput bernama Surya Kencana pukul 10.45 pagi. Seharusnya, di Surya Kencana inilah semalam kami berkemah, tapi sesuatu di luar kendali terjadi. Dan seharusnya, di Surya Kencana ini terdapat pemandangan yang sangat indah, padang rumput bernuansa keemasan berpadu dengan sinar matahari, dengan bunga-bunga edelweis yang tumbuh suka-suka hampir di seluruh hamparan. Tapi nyatanya, badai kembali mengacau, angin berembus kencang-kencang. Para lelaki mengisi persediaan air kami di sungai Surya Kencana. Semua orang memasang kaos kaki, sarung tangan dan masker mulut karena angin kabut yang berembus semena-mena.
Kami berjalan dari Surya Kencana Barat menuju Surya Kencana Timur. Kabut dan embun menjilati muka kami dengan liur yang beku, meninggalkan Kristal-kristal di setiap helai bulu mata dan alis kami. Dingin. Namun kali ini dinginnya tidak menggigit, dinginnya membelai. Jangkauan pandangan pun kini terbatas, karena kabut membuat semuanya jadi serba buram.
Surya Kencana berakhir, dan kami kembali masuk ke dalam hutan. Saya tergelincir beberapa kali, tangan saya kembali membeku karena saya harus menggenggam pepohonan supaya tidak tergelincir, pepohonan yang basah dan dingin. Hujan pun kembali turun, turun berkali-kali, dengan jeda yang sangat sempit. Saat berjalan menurun, capeknya enggak terasa, beda dengan mendaki. Tapi tiap kali saya berhenti sejenak buat memilih jalan yang aman, dengkul saya bergetar enggak karuan karena dari tadi dieksploitasi untuk menahan beban badan saya.
Matahari kini tepat di atas kepala, namun sinarnya tidak berhasil sama sekali menghangatkan tubuh kami, kalah oleh hujan. Waktu makan siang pun tiba tepat kami sampai di pos ke-5, sebuah dataran. Akrima kembali memasak, saya menunggu dalam beku dan kantuk, lagi-lagi Hana yang menjaga saya agar tetap terjaga.
Selesai makan siang, sekitar pukul 2 siang kami melanjutkan perjalanan turun, perjalanan yang saya kutuk. Karena saya mulai lagi mengeluh, lama-lama saya merasa marah. Tidak banyak yang dapat saya ceritakan di sini, karena saya benar-benar marah, dan putus asa. Dinginnya kembali menggigit, tangan kami membengkak—usaha tubuh menghangatkan badan dari suhu dingin yang ekstrem—jari-jemari tidak dapat dikepal, seluruh gerakan terbatas dan kaku, dan rasanya perjalanan menurun ini tidak ada ujungnya. Saya mulai menangis diam-diam, tanpa air mata, tanpa suara, karena—lagi—saya benar-benar marah.
Saya tetap berjalan dan berjalan, kaki saya rasanya mau copot, dan hujan yang dari tadi tidak mau berhenti dengan berhasil membekukan tubuh saya. Waktu terus berjalan dan perjalanan ini rasanya benar-benar enggak berujung. Saya, Fatah, Hana, dan Pak Suryo di depan, berjeda cukup jauh dari yang lain. Pos demi pos sudah kami lewati, di pos 2 (pos dihitung mundur, setelah pos 5 tempat kami makan siang) medannya berganti lagi, yaitu merupakan tangga batu-batuan. Harusnya ini merupakan ide bagus tapi nyatanya tangga batu malah makin menyiksa kaki saya yang sudah enggak kuat menahan beban badan. Saya terpeleset berkali-kali.
Setelah tangga batu yang sangat panjang dan menyiksa tadi, medan berganti lagi karena kami sudah tiba di bawah, sudah keluar dari lebatnya hutan. Kini medannya merupakan turunan landai sempit bertanah lembap dan berkerikil, disamping kanan kiri merupakan hamparan luas sawah dan perkebunan wortel juga daun bawang. Di sini saya masih marah karena suhu dingin yang masih membengkakkan telapak tangan saya, juga karena kata orang-orang bahwa bila sudah sampai di sawah maka jalan menuju akhir tidaklah lama lagi yang ternyata adalah kebohongan besar. Jalan ini lagi-lagi tidak berujung. Semua ini membuat saya gila. Fatah dan Hana mengetahui perasaan tertekan saya, mereka juga mengerti karena ini kali pertamanya saya mendaki gunung, maka mereka tiada hentinya menyemangati saya. Sambil uring-uringannya saya terus melangkah, dengan seluruh rasa sakit dan amarah yang berusaha saya abaikan.
Bersambung: Memeluk Asa Menuju Puncak Gunung Gede Bersama Carvedium (Bagian III)