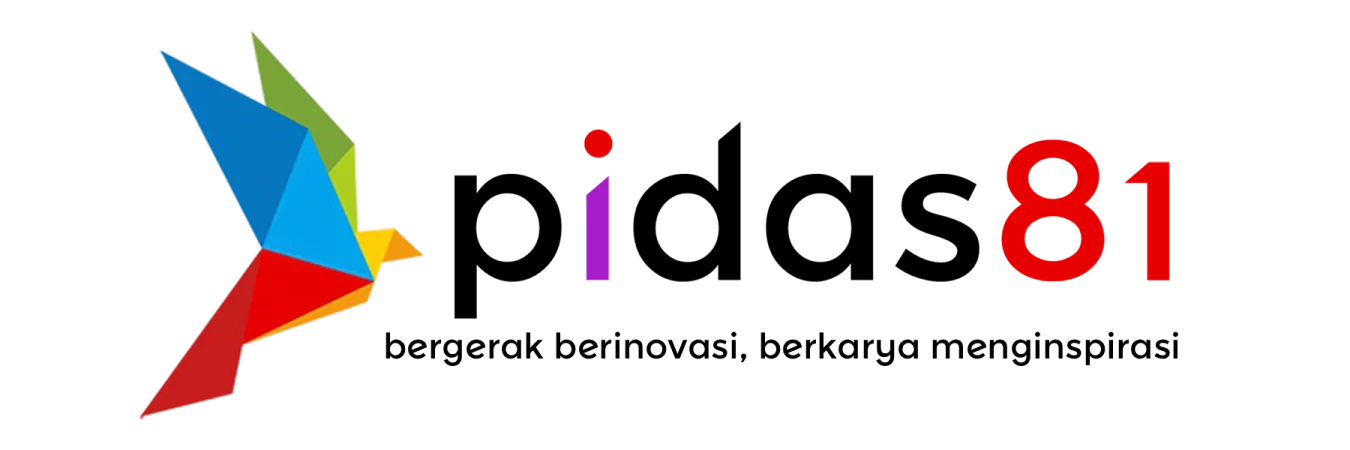Sulawesi Utara, “ tempat Nyiur Melambai”, adalah saksi nyata dari lini kehidupan seorang wanita dengan garis mata yang teguh dihantam ombak dan serpihan karang, namanya kerap diagung-agungkan publik, namun tak dipuja demikian rupa seperti layaknya pahlawan-pahlawan lain. Maria Walanda Maramis ialah namanya, personifikasi perempuan yang tabah serta penuh kobaran api. Ia pertama kali melihat wujud dunia di Kema, kota pelabuhan kecil, pada tanggal 1 Desember 1872.
Maria tidak mewarisi setetespun darah ningrat, memang, pamannya adalah seorang tokoh politik dengan pangkat setara bupati. Namun kedua orangtuanya adalah pedagang di pesisir pantai, mengingat tempat kelahirannya adalah kota pelabuhan. Saat umurnya masih enam tahun, wabah kolera menyerang Sulawesi, Asiatic cholera, wabah ganas yang memakan habis sistem pencernaan semua orang yang terkontaminasi dalam hitungan jam, juga turut menyerang kedua orangtua Maria. Sejak itu juga, Maria diurus oleh pamannya.
Tentu saja, sebagai seorang tokoh politik yang dihormati khalayak luas saat itu, paman Maria, yang bernama Mayor Ezau Rotinsulu mampu membiayai pendidikan Maria dan kakak perempuannya, walau hanya di sekolah rakyat biasa dengan kurikulum yang terbilang kurang memadai. Hal ini didasari oleh dua faktor penting, pertama, karena warisan dari kedua orangtua Maria hanya cukup untuk membiayai kakak laki-lakinya untuk bersekolah di sekolah tinggi. Kedua, dikarenakan adat Minahasa yang menganggap perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, oleh sebab itu, akses pendidikan perempuan sangat kurang.
Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali Maria meminta pamannya untuk menyekolahkannya di Meisjesschool, sekolah untuk perempuan dengan bahasa pengantar Belanda. Gagasan tersebut selalu ditepis dengan tegas oleh pamannya, tanpa Maria harus repot-repot menjelaskan argumentasinya terlebih dahulu. Maria pun semakin jauh dengan impian pendidikan intensif yang selalu didamba-dambakan sedari ia kecil.
Sejatinya kejadian itu memang destruktif, namun tak terlalu mendistraksi Maria untuk meraih mimpi-mimpinya. Dia berpikir begini, bahwa kalau ia punya sedikit privilese sebagai keponakan orang terpandang, mengapa ia tak belajar saja dari kenalan-kenalan pamannya? Pamannya acap sekali menerima tamu di rumahnya, biasanya tamunya juga merupakan petua-petua maupun tokoh Belanda yang memiliki peran yang cukup penting. Jadi, Maria mulai belajar sedikit-sedikit perihal tata cara menyambut tamu, mempersiapkan jamuan untuk tamu, sampai cara beretika sopan santun.
Detik demi tahun berlalu, Maria tumbuh menjadi remaja yang disenangi di antara khalayak sekitar rumahnya. Banyak pria yang berdatangan ke rumah pamannya, dengan iming-iming bersilaturahmi, yang setelah ditelusuri, mempunyai keinginan untuk meminang Maria sebagai istrinya. Banyak dari pria itu yang ditolak mentah-mentah oleh Maria, sampai akhirnya, ia bertemu pandang dengan Jozep Frederik Calusung Walanda, seorang guru yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di daerah Ambon. Percikan dalam hubungan mereka pun semakin intens tiap minggunya, sampai akhirnya Jozep mendapat restu dari paman Maria untuk menikahinya.
Pesta pernikahan berakhir, bunga-bunga yang terangkai indah di lokasi pernikahan pun layu, dan Maria dikadokan oleh ribuan lembaran kehidupan baru yang tak sabaran, menunggu untuk cepat-cepat diisi. Maria pun lekas pindah ke desa kecil yang jauh dari keramaian bersama dengan suaminya, Maumbi namanya. Desa yang terbagi perbatasannya dengan daerah ibu kota Manado.
Statusnya sebagai seorang wanita yang sudah menikah, lantas tak membuat semangat Maria untuk belajar langsung rontok dan tak tersisa akar-akarnya begitu saja. Ia justru aktif menyuarakan segala oktafnya di surat kabar Tjahaja Siang, surat kabar milik redaksi di daerah Manado. Maria banyak menulis tentang peran perempuan, ibu, sampai berani menyorot sedikitnya pendidikan yang aksesibel bagi seorang perempuan.
Selain itu, di lingkungan desanya yang baru, Maria berkenalan dengan Ibu Ten Hoeve, seorang wanita berkewarganegaraan Belanda, saleh perilakunya, baik tuturnya. Begitu baik sampai ia bersedia mengajari Maria tentang hak serta kewajiban perempuan, sopan santun, cara berpakaian, dan berbagai hal lainnya. Maria pun mulai tertarik, sampai akhirnya ibu Ten Hoeve mengajarinya tentang ilmu kesehatan, cara mendidik dan membesarkan anak, ilmu disiplin serta ilmu ketertiban, dan lainnya.
Maria merasakan gejolak yang membuncah bahwa ilmu yang ditimba olehnya ini harus disebarkan ke wanita-wanita lain, terutama perempuan muda yang tidak bisa mengakses pendidikan secara maksimal, dan juga kepada perempuan yang dibesarkan dalam kentalnya adat Minahasa yang kurang lebihnya melarang perempuan untuk mengejar setinggi-tingginya pendidikan.
Perpisahan pahit, ini nyata-nyatanya dari kehidupan pendek manusia yang tak luput darinya. Kemanapun perginya, perpisahan akan selalu mengejar. Begitulah tragedi yang terjadi antara Maria dengan Ibu Ten Hoeve yang lembut hatinya itu. Ibu Ten Hoeve harus ikut suaminya pulang ke Belanda, sedangkan Maria, dengan segala tarikan kewajiban suaminya yang mengabdi sebagai seorang pengajar, harus pindah ke hiruk pikuk kota Manado untuk mengajar sekolah Belanda.
Surat demi surat Maria kirim kepada sekolah Belanda tempat suaminya mencari nafkah sebagai guru, semuanya ditolak dan tidak diberikan perhatian lebih. Sampai akhirnya Maria pun, dengan otak cerdasnya memutuskan untuk mendirikan PIKAT, “Percintaan Ibu Kepada Anak Penurunnya”
PIKAT ingin perempuan-perempuan Minahasa untuk lebih mengenal satu sama lain, lantaran semuanya kurang lebih harus menanggung nasib yang sama, sejelek-jeleknya nasib sebagai seorang perempuan di masa kolonial, serta menyiapkan perempuan untuk berani secara lantang mengutarakan keinginannya sendiri. Segala peluh yang dikeluarkan oleh Maria dibayar puas, sekolahnya makin gemilang, bahkan sampai dikunjungi Gubernur Hindia Belanda.
Politik dan pendidikan, tentu keduanya bersinggungan. Maria pun berjuang agar wanita mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum, hal ini berbuah manis, pada tahun 1921, pihak Belanda mengizinkan perempuan untuk menyuarakan suaranya dalam pemilihan umum.
Saat tubuhnya mulai renta, dan sakit sudah menyerang kerangkanya, Maria masih aktif surat-menyurat pada anggota PIKAT. Sampai akhirnya, di akhir napas yang ditarik olehnya, Maria berhasil membisiki Nyonya Sumolang, salah satu anggota PIKAT mengenai satu hal.
“Jagalah dan peliharalah baik-baik, anak bungsuku PIKAT”