Saya duduk di sebuah café, sendirian. Karena saya sedang jenuh dan pikiran saya sedang kusut. Maka saya memutuskan untuk pergi sejenak dari rumah atau pun gedung-gedung, dan memilih bangunan mungil untuk sekadar menyeruput kopi.
Kebiasaan mengkonsumsi kopi mengalir berlebihan dalam diri saya. Secangkir kopi tidak menenangkan saya, gagal memanjakan lidah saya tepatnya. Tapi pada akhirnya, saya menemukan sebuah percakapan yang menarik dua indra saya untuk menyimak.
Sebelum saya menulis kalimat demi kalimat selanjutnya, ada baiknya saya memberitahu bahwa sepertinya saya salah menyebutnya ‘percakapan’, ini lebih ke monolog. Well, atau mungkin ini awalnya sebuah percakapan, di mana terlibat dua orang atau lebih yang saling bicara. Namun mungkin ini menjadi sebuah monolog bilamana saya mulai menyimak.
Perempuan itu biasa saja. Saya tidak bisa menafsir usianya. Namun berikut perawakannya, silakan menilai sendiri. Ia tinggi, jenjang. Pinggulnya lebar, ideal, bokongnya tipis. Pinggangnya menyekung, indah. Jarinya lentik, namun pendek. Ia memakai pakaian yang secara keseluruhan berwarna monoton, tidak ada ledakan warna terlihat di pakaiannya, semua senada, pastel.
Wajahnya pasaran, matanya tergolong kecil, namun tidak sipit. Hidungnya rata dan meruncing di bawah, untungnya. Bibirnya tebal dan cukup lebar. Semua telanjang tanpa terbalut bedak atau gincu.
Lawan bicaranya, lelaki berambut ikal hitam lebat. Dia bukan lelaki yang cukup tinggi. Saya tidak terlalu memperhatikan wajahnya, tapi yang pasti saya tidak bisa melupakan irisnya yang berwarna coklat bulu rubah.
“Suatu hari ada orang nanya ke gue, apa sexual orientation itu penting bagi gue? Terus gue jawab, ya tentu penting.”
Inilah kalimat awal yang menelusup melalui daun telinga saya, dan menggetarkan gendang timpani saya.
“Orang itu lanjut nanya, apa orientasi seksual gue, karena dia menemukan gue ga janggal dengan pasangan-pasangan homoseksual. Nah, sejak itu gue juga mulai merenungkan, sebenernya apa opini gue dan apa sebenernya perasaan gue terhadap masing-masing orientasi seksual yang beragam.”
Demikian kalimat selanjutnya yang terlontar dari bibir tebal dan lebar perempuan itu, yang menarik perhatian saya lebih lagi.
“Sejujurnya gue tentu straight, gue enggak pernah pacaran sama perempuan, dan enggak pernah memiliki ketertarikan serius dengan perempuan. Tapi, sebenarnya ketertarikan sepele tentu sering terjadi,” ujar perempuan itu sambil menatap lekat lelaki di hadapannya.
Sialnya indra pendengaran adalah satu-satunya indra tanpa pelindung, menurut saya. Mata memiliki kelopak bila kita tidak mau melihat. lidah memiliki rongga mulut bila kita tidak mau merasa. Kita dianugerahi kemampuan menahan nafas saat kita tidak mau mencium. Juga otot yang bersedia memindahkan anggota badan apabila kita ingin menghindar dari sentuhan. Namun telinga? Kita tidak bisa menolak kecuali kita mau dengan bodoh menyumbat lubang telinga kita dengan jari, atau kecuali kalau kita tuli.
“Gue bukan homophobic sama sekali, yaitu orang yang sangat jijik dan menentang homoseksualitas. I think, why not?”
Itulah kalimat kesekian yang perempuan itu ucapkan, yang dengan liar memburu telinga saya. sekali lagi saya mengutuk telinga saya.
“Entah kenapa gue mengerti perasaan gay couple atau lesbian couple. Karena mereka menemukan kenyamanan dan keindahan pada seseorang, terlepas dari gender orang itu sendiri. So again, I think, why not?”
Dan inilah kalimat terakhir dari perempuan itu sampai akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan telinga saya. Mari kita simak monolog gadis itu dengan ikhlas.
“Waktu itu gue mulai meragukan apa gue seorang biseksual, dan lama kelamaan gue takut. Apakah itu akan jadi terlalu tabu bagi orang lain yang menemukan gue bisa tertarik dengan perempuan? Setelah itu gue mulai baca-baca tentang homoseksualitas, dan mulai memperhatikan sikap-sikap gue yang berhubungan dengan hal ini. Dan pada akhirnya, gue mengakui pada diri gue sendiri, bahwa gue bisa tertarik secara estetika, emosional, atau seksual kepada seseorang terlepas dari gender-nya. Ya kurang lebih begitu.”
Perempuan itu mengakhiri kalimatnya dengan menyambut sedotan pada segelas kopi dinginnya, yang saya yakini terlalu manis. Saya mulai berpikir, jadi perempuan itu bisa jadi biseksual, bahkan dia mengakuinya.
“Maksud gue, kenapa orang harus mikirin gender saat kita bisa nyaman senyaman-nyamannya sama seseorang? Orang terlalu nyambungin homoseksualitas dengan melakukan hubungan itu, zina maksud gue. Orang yang pacaran sama sesama jenis murni karena cinta dan enggak ngelakuin hal itu juga ada kan? Dan menurut gue itu enggak masalah. Atau lo bisa bilang, gue sangat open-minded dengan hal itu.”
Sial! Pernyataan perempuan itu terlalu menarik. Dan sialnya lagi, kopi saya sebenarnya sudah habis. Tuhan, apa yang saya lakukan disini selain menguping?
“Kalau ngomongin realitas, gue memang enggak pernah jatuh cinta sampai kepincut dan pedekate-in perempuan. Tapi yang jelas, gue pernah merasa nyaman banget sama perempuan, gue biarin dia tidur di tubuh gue, sesuka yang dia mau. Dia pernah mencium pipi gue dan gue merasa tergetar. Gue peduli dengan dia, dan gue menemukan keindahan di dirinya. Mungkin dia juga merasakan rasa nyaman yang sama kaya yang gue rasain, tapi dia dengan mudah menyebutnya ‘persahabatan’, sedangkan gue, kembali berkutat dengan pergolakan hati dan mempertanyakan orientasi seksual gue.”
Wow, itu pengakuan yang cukup berani, kan? Dan takdir atau bukan, kenapa Tuhan membiarkan saya menyimak percakapan ini dengan begitu nyata dan mulus? Saya mengakui, saya sangat tenggelam dalam monolog perempuan ini.
“Tapi lama-lama itu memudar, dan gue akhirnya menemukan seorang cowok yang sekarang adalah mantan pacar gue. Dan gue bener-bener sayang sama dia waktu itu. Sekarang setelah gue dewasa gue bisa menyimpulkan, bahwa gue bisa jadi biseksual. Tapi tetep, 78% ke laki-laki, dan hanya 22% ke perempuan. Gue mungkin bisa suatu hari bener-bener merasa nyaman dengan perempuan, dan gue enggak masalah untuk macarin dia kalau memang dia pantas dan gue enggak bisa lepas dari dia, tapi gue enggak bakalan jadiin itu serius. Gue enggak bakal sampai menikahi dia atau semacamnya. Gue cuma menyalurkan perasaan gue yang gue anggap itu enggak masalah, asal gue enggak berzinah kan. Jadi bisa dibilang gue dan cewek gue itu adalah sahabatan, dengan status pacaran. Konyol atau enggak, kadang status itu penting.”
Perempuan itu mengaduk-aduk gelas raksasanya dengan sedotan, menyatukan krim yang pecah. Sedangkan lelaki penyimaknya, masih menatap perempuan itu. Saya pun begitu. Saya menuntut sebuah akhir.
“Tapi tentu gue perempuan beragama, dan agama gue menentang keras homoseksualitas. Jadi pada akhirnya gue bakal berusaha membatasi diri, untuk tetap enggak selalu membenarkan homoseksualitas itu sendiri, dengan cara menahan diri gue agar enggak jatuh cinta dengan perempuan, yang mana kesempatan terjadinya juga kecil. Bersyukurnya ya mantan-mantan gue, percayalah mantan gue cukup banyak, itu laki-laki semua. Dan gue harap biseksualitas gue bakal hilang, karena gue tau, akan tiba suatu hari di mana perempuan berwujud lelaki dan lelaki berwujud perempuan dan semakin banyak orang memaklumi hal tersebut, itulah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Jadi itulah cerita gue tadi, gue memang enggak membenci homoseksualitas, tapi gue tau itu salah, walaupun gue bisa dibilang salah satu dari mereka. Dan gue dalam tahap mencoba untuk berhenti membenarkan hal tersebut. Cuma gue enggak terima aja banyak orang yang langsung menghakimi orang-orang dengan orientasi seksual yang kayak gitu… bilang mereka menjijikkanlah, terus main nge-bully… semua kan ada alasannya. Dan untuk menilai sesuatu, enggak bisa selalu dari kacamata kita. Orang bolehlah nge-judge, tapi untuk mengucilkan dan memperlakukan mereka dengan enggak adil menurut gue adalah salah besar.”
Itulah akhir dari monolog perempuan itu, yang syukurnya memiliki pendengar—si lelaki berambut ikal.
Monolog yang saya simak baik-baik.
Monolog yang saya coba tulis dengan jujur.
Monolog yang tidak saya pihak ke belah manapun.
Monolog yang saya tulis tanpa mencari kebenaran atau kesalahannya.
Monolog yang saya terima sebagai data, bukan sebagai yang saya percaya.
Nah, di sini yang cukup ambigu.
“Apakah lo pikir sudut pandang dari sebuah cerita perlu diperhitungkan?” Tanya perempuan itu.
“Semua hal bisa jadi a total manipulation kalau orang merasa kurang aman” jawabnya sendiri.
Mereka pun memanggil pelayan dan menuntaskan tetek-bengek tagihan. Saya lihat mereka masuk kedalam satu mobil.
Apakah sudut pandang dari sebuah cerita perlu diperhitungkan? Saya berpikir sendiri.

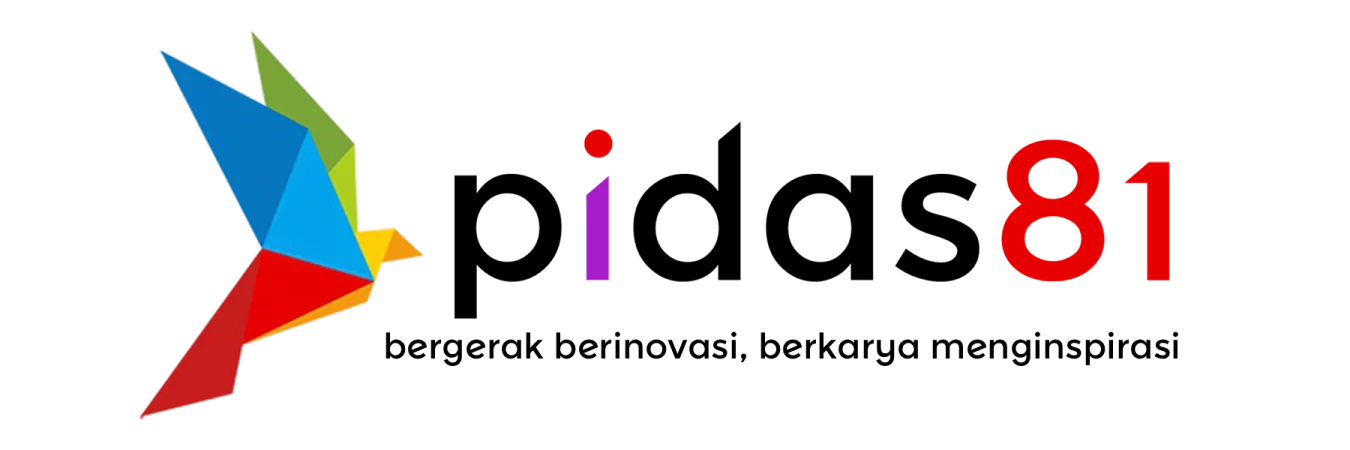

Gue mau komen, ternyata Niken lagi. wkwkwk.
Jaman skrg org ngomongin LGBT dimana-mana ya..
Ini anak didikan Kak Fauzan abis-__- Kalau udah deket-deket Kak Fauzan emang rasanya ada aja urusan sosial.
oh, ya, komentarnya, ini pernah disodorin kakak gue dulu, “Selamat datang di dunia nyata, dimana hitam dan putih bercampur.
Ketika kita disodorkan abu-abu.”
Tuh kan, kok lo suudzon sih sama gue Dur? Pasti gue selalu disangkutpautkan deh, hahaha! Ih, tapi ini bukan kemauan gue, ya… gue hanya mendorong Dur, supaya menulis, dan isu-isu sensitif kayak gini emang ya… ya emang sensitif sih #gajelas
Itu quote-nya Nasrul? Apa kakak lo yang lain?
wkwk iya kak, iyaa. Tapi kurang lebih kan memang begitu. Ketika aura anak sosialnya keluar dr kakak, wkwk. Terus omongannya nyambung ke “Ini loh Indonesia”. Jadinya yang awalnnya cuma ngerti apa yg trjd, jadi ngeh, dan berani menyuarakan. Ya bagus kok bagus kak.
iya quotesnya kakak yg fakultasnya paling berhubungan dengan aktivis. Tapi dikerenin dikit. Intinya sih gitu. Sekali-kali kakak saya ngeluarin kalimat keren bisa lah. Walaupun kemungkinan besar doi udah lupa
Niken awesome! Lovely writing! Pemilihan kata lo pas sekali….
duh dur!
kayaknya artikel gue magnet banget buat lo yah..
gue emang udh concerned sama masalah LGBT dari awal kelas 11,
dan bisa dibilang gue cukup open-minded dan menoleransi hal itu dengan segala rasa pengertian gue terhadap mereka.
hmm… hitam, putih, ataupun abu-abu sama-sama warna kok, yang penting mereka sejati dan bersih 😉
*
makasih yaaa marsanti <3
i'm watching you.
(O_o)
Bukan ken, gue tau banget ini si Durra pasti emang matanya ngelirik tulisan-tulisan yang bikin pro-kontra, dan… kebetulan tulisan lo rata-rata mengundang pro-kontra, seperti yang satu ini, ditambah dengan cara lo menulisnya, hahaha!
Tapi gue sendiri masih penasaran ken, apa yang membuat lo concern sama masalah LGBT ini? Terus posisi lo dalam hal ini apa? Sebagai orang yang mendukung, membolehkan, atau netral? Yang pasti lo bukan yang 100% enggak setuju, dan gue rasa lo juga bukan yang netral banget, hahaha! Walau sebenernya cukup terbaca dari statement terakhir bahwa hitam, putih, abu-abu itu sama-sama warna (walau pasti banyak yang bilang juga bahwa ketiga warna itu bukan warna sebenarnya, jadi enggak masuk hitungan, hehe).