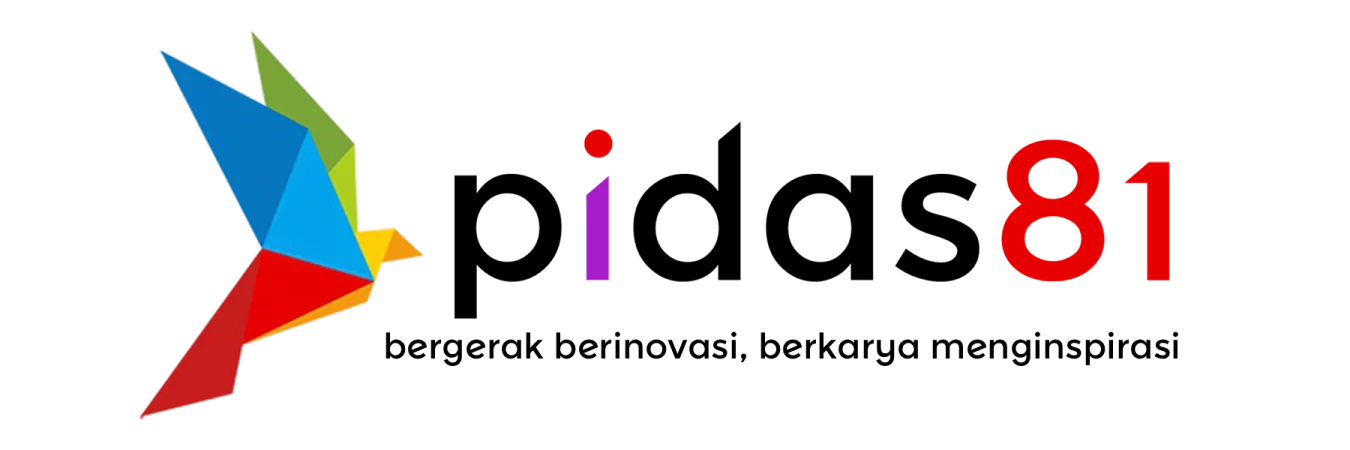Gelora teriakan dari seantero kota membuat darahku kian mendidih. Entah mata ini telah buta, atau telinga ini telah tuli, tapi kami semua tak peduli meski ribuan derap langkah prajurit Belanda berlari-lari mengejar kami. Jangan lupakan runtutan bunyi tembakan dan jeritan yang seharusnya begitu menggilas keberanian. Namun rupanya denyut nadi kami tak kunjung berhenti, justru terik matahari yang melelehkan keringat kami semakin membarakan semangat dari lubuk hati.
“Lari ke sana!” telunjuk pria di sampingku teracung pada arah jam 10. Belum sempat aku membelokkan kaki, dia telah menggeret lenganku menuju tempat yang ditunjuknya. Sebagian orang berlari mengikuti kami, bersembunyi di balik separuh bangunan rumah yang nyaris lebur akibat ledakan senjata api, sisanya berpencar entah kemana. Dari sudut penglihatan mataku, kulihat dua orang tewas tertembak lagi sebelum sempat bersembunyi. Ya Tuhan, kapan semua ini berakhir? Mataku sampai tak sanggup berair lagi sebab semuanya telah kuhabiskan dua minggu terakhir, sejak pertama kali ultimatum untuk meninggalkan kota kelahiranku itu dikumandangkan.
“Dengar semuanya!” pria tadi, yang memimpin kelompok kami, berseru pelan saat kami semua sudah terduduk lemas. Sekitar sebelas orang menatapnya penuh takzim. “Ini bukan lagi tentang hidup dan mati. Ini tentang memperjuangkan bangsa ini dari mereka yang tak pernah berhenti menyiksa kita. Kita tunjukkan bahwa kita tidak takut! Kita akan lawan!” aku tahu napas pria paruh baya itu terengah-engah, aku tahu sorot mata itu takut akan terpejam selamanya sebelum sempat melihat kemerdekaan bangsa ini, tapi aku tahu getar suaranya penuh hasrat ingin mencapai sebuah bintang yang seharusnya kami raih.
Salah seorang dari kami merangkul dua orang di kanan kirinya, seketika rangkulan itu menyambar di antara kami yang memang duduk melingkar meski tak beraturan. Kami bersebelas saling tatap, aku yang pertama kali mengangguk meyakinkan semuanya. Pria paruh baya di sampingku itu turut mengangguk, lantas yang di sebelahnya ikut serta, dan seperti rangkulan tadi, anggukan saling meyakinkan itu menyebar.
“Sekarang kita bangkit lagi, kita lawan mereka semua lagi dengan senjata dan tenaga kita yang tersisa. Setuju?” kini seorang pemuda yang usianya mungkin 10 tahun lebih tua dariku bersuara, berbalas anggukan dari kami sebagai pendengar.
Kaki kami bangkit kembali, sebagian mengatur napas demi melanjutkan perjuangan, sebagian lagi berpelukan. Termasuk diriku, yang tiba-tiba saja mendapat pelukan penuh kasih dari sang pria paruh baya. Di situlah air mata yang kukira telah kering berurai lagi. Tidak, sungguh aku tidak takut mati demi bangsa ini. Barangkali yang kutakutkan hanyalah mati meninggalan pria itu, atau justru pria itu yang tewas meninggalkanku.
“Nang,” tangan kekarnya menepuk-nepuk bahu bidangku setelah ia melepaskan pelukannya, “kalau Bapak mati dan kamu masih hidup, ceritakan kepada Bapak melalui senja tentang bagaimana kehidupan negara ini setelahnya, yo?” suara paraunya telak menggetarkan hatiku. Gendang telingaku benar-benar tidak siap mendengarnya.
Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Kugenggam tangannya yang terlihat tak lagi muda sebab aku gengsi memeluk Bapak, “Kalau aku yang mati duluan piye, Pak?”
Duarr! Detik itu juga, ketika kulihat Bapak mengangkat mulutnya, suara tembakan dahsyat mendobrak memasuki indra pendengaranku. Terdapat pula beberapa orang Belanda berbicara sebelum akhirnya mereka meninggalkan tempat persembunyian kami. Aku tidak tahu mereka pergi ke mana, yang aku tahu hanyalah langit itu biru. Terang dan lembut, dengan awan tipis berjarak yang menggantung. Matahari telah mencondongkan dirinya ke barat, syukurlah ia tidak tepat di atas langit ketika penglihatanku bersisa sedikit. Aku masih dapat merasakan genggaman Bapak menenangkan jiwa setengah matiku. Sekujur tubuhku sakit, pikiranku berlarian tatkala ragaku terkulai tiada daya, mataku perlahan lelah melihat hamparan langit itu. Aku mengantuk, mungkin Bapak di sebelahku pun sudah tertidur. Akankah kami berdua menyusul Ibu dan Adik? Berbahagia lagi dalam meja makan dengan empat kursi?
Mataku terpejam cukup lama, diriku seolah dibawa terbang oleh sebuah arus kuat menuju negeri entah berantah. Aku tidak peduli siapa yang membawaku. Prajurit Belanda, sesama rakyat negaraku, atau malaikat pencabut nyawa sekalipun, aku tidak peduli. Biarlah jiwaku dibawa pergi, meninggalkan ragaku yang bersedia tergeletak demi memperjuangkan bangsa besar ini.
Namun, sebuah tepukan kencang di punggung seakan menyerap kembali seluruh kesadaranku. Mataku kembali terbuka, walaupun yang kulihat bukanlah hamparan langit biru beserta manusia-manusia penuh darah yang berserakan. Ini perpustakaan sekolah, aku terduduk di salah satu kursinya, dan di hadapanku terdapat laptop yang masih menyala.
“Woi, katanya mau merayakan ulang tahun sama keluarga di rumah, kok jam segini bintang utamanya malah belum pulang dari sekolah sih?” lelaki berseragam putih abu itu berdiri di sisiku, tas ransel telah bergelantung manis di pundaknya. Kulirik jam di laptop, pukul 17.18. Astaga!
“Ah! Lu kok enggak bangunin gua, sih?” aku langsung sewot, buru-buru kubereskan semua peralatanku. Temanku menggeleng-gelengkan kepala, ditepuknya bahuku penuh lembut. Aku terdiam. Tepukannya persis seperti tepukan pria paruh baya yang dulu kupanggil ‘Bapak’.
“Oke deh, enjoy your time, Tyo. Gua duluan ke parkiran ya, lu cuci muka dulu gih.” segera ia beranjak dari perpustakaan, membiarkanku kebingungan atas perasaanku. 79 tahun yang lalu, saat kulihat langit yang terakhir kalinya pun, aku berulang tahun yang ke-17.